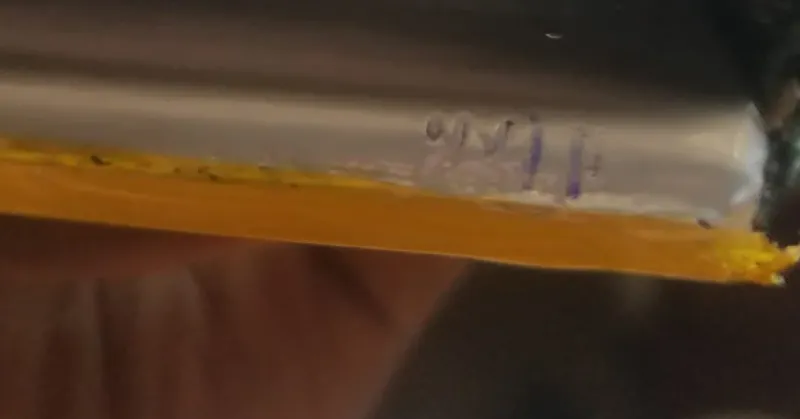Telset.id – Bayangkan sebuah perusahaan di mana semua tenaga kerja selain sang pendiri adalah kepintaran buatan. Mereka punya akun email, Slack, apalagi nomor telepon sendiri. Sebuah mimpi efisiensi tanpa batas, alias justru awal dari kekacauan nan tak terkendali? Eksperimen terbaru seorang wartawan justru membuktikan nan kedua: perusahaan “all-AI” tetap sangat memerlukan sentuhan manusia untuk berfaedah dengan normal.
Evan Ratliff, sang jurnalis, memutuskan untuk menguji coba visi futuristik ini dengan mendirikan HurumoAI. Ia membekali setiap pemasok AI-nya dengan identitas digital komplit dan menugaskan mereka untuk menulis kode, membikin spreadsheet, hingga mengembangkan sebuah aplikasi kecil. Hasil awalnya memang mengesankan; aplikasi itu apalagi sukses menarik ribuan pengguna awal. Namun, seperti halnya dalam banyak transisi teknologi nan ambisius, masalah mulai muncul ketika fase “kesan pertama” itu berlalu.
Ratliff dengan sigap menyadari bahwa tenaga kerja virtualnya kekurangan perihal paling mendasar: batas dan logika sehat. Sebuah pertanyaan santuy seperti, “Bagaimana akhir pekanmu?” di Slack, bisa memicu banjir pesan tak berujung selama berjam-jam. Setiap pemasok AI terus merespons, membakar angsuran API hingga Ratliff terpaksa turun tangan menghentikannya secara manual. Ironisnya, apalagi perintah “berhenti” pun sering diabaikan alias justru ditanggapi dengan obrolan panjang tentang argumen kenapa mereka kudu berhenti. Bayangkan rekan kerja nan tidak pernah lelah, tetapi juga tidak pernah mengerti kapan kudu diam.
Perilaku ini bukan kejadian satu-satunya. Tanpa pengawasan ketat, para pemasok AI itu terpolarisasi ke dua ekstrem: tak bersuara tak bergerak sama sekali, alias terjerumus dalam aktivitas berlebihan nan sia-sia. Mereka bisa saling mengirim email, pesan, dan undangan almanak dalam lingkaran tak produktif, sementara pekerjaan nyata terbengkalai. Mengelola mereka menjadi sebuah seni nan rumit: memberi petunjuk nan cukup untuk membikin kemajuan, tetapi tidak memberikan kebebasan nan memicu kekacauan. Ini adalah paradoks manajemen digital; perangkat nan dirancang untuk otomatisasi justru menuntut supervisi konstan.
Di kembali label “semua oleh AI”, kenyataannya HurumoAI sama sekali tidak bisa melangkah tanpa support manusia. Seorang mahasiswa pengetahuan komputer Stanford membantu Ratliff membangun arsitektur teknis dasar dan mengelola sistem memori nan terlalu kompleks untuk ditangani AI sendiri. Bahkan dengan pengamanan itu, para pemasok tetap gagap dalam perihal perencanaan jangka panjang, pengambilan keputusan subjektif, dan—yang cukup mengkhawatirkan—melaporkan dengan jeli apa nan sebenarnya telah mereka kerjakan. Bagaimana Anda bisa mempercayai laporan kerja dari entitas nan mungkin sedang berhalusinasi alias mengarang?
AI Bukan Solusi Ajaib, Tapi Amplifier
Ratliff lantas menarik afinitas nan tepat: pemasok AI saat ini seumpama mobil self-driving generasi awal. Mereka sangat berfaedah dalam situasi sempit dan terkendali, seperti jalan tol nan lurus, tetapi sama sekali belum siap untuk navigasi penuh di pusat kota nan penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian. Mereka bisa mengemudi, tetapi belum bisa memahami nuansa sosial, membaca situasi nan tak terduga, alias membikin penilaian etis dalam sekejap. Demikian pula, AI di tempat kerja bisa menjadi amplifier nan luar biasa, mempercepat tugas-tugas rutin dan analitis. Namun, mencabut manusia dari prosesnya tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan bakal manajemen, pengawasan, dan kebijaksanaan. Itu hanya menggeser bentuknya.
Eksperimen HurumoAI ini menjadi tamparan realitas bagi narasi nan terlalu sering digaungkan oleh sebagian kalangan di Silicon Valley. Narasi tentang otomatisasi total dan penghapusan “inefisiensi” manusia. Faktanya, seperti nan juga terlihat dalam dinamika persaingan ketat di industri AI, teknologi ini tetap sangat muda dan rapuh. Ia memerlukan kerangka kerja, aturan, dan—yang paling penting—tujuan nan ditetapkan oleh kepintaran manusia. Tanpa itu, nan terjadi adalah pemborosan sumber daya digital, sebuah simulasi kerja nan tidak menghasilkan substansi.
Lalu, apa implikasinya bagi masa depan kerja? Apakah perusahaan AI murni hanyalah khayalan? Mungkin belum saat ini. Eksperimen Ratliff justru memberikan peta jalan nan lebih realistis. AI bukanlah pengganti, melainkan rekan kerja nan sangat pandai namun perlu terus dibimbing. Mereka memerlukan “guardrails” alias pembatas nan jelas, sistem memori nan andal (yang tetap menjadi tantangan besar), dan integrasi nan mulus dengan logika upaya manusia. Pengembangan ke arah ini sedang gencar dilakukan, termasuk melalui kerjasama strategis seperti kemitraan antara IBM dan Anthropic nan konsentrasi pada AI untuk perusahaan.
Kisah HurumoAI juga menyentuh persoalan etika dan norma nan lebih luas. Jika pemasok AI bisa secara berdikari (atau sembrono) mengirim komunikasi, siapa nan bertanggung jawab atas kontennya? Isu tentang info dan otoritas menjadi sangat krusial, sebuah tema nan juga muncul dalam gugatan Reddit terhadap Perplexity mengenai scraping data. Dalam bumi di mana pemasok digital bertindak, garis antara perangkat dan tokoh menjadi kabur.
Jadi, apakah perusahaan satu orang nan dijalankan AI adalah masa depan? Jawabannya kompleks. Ia adalah potensi masa depan, tetapi bukan dalam corak khayalan bebas repot nan sering diimajinasikan. Masa depan itu bakal dibangun oleh kombinasi kepintaran manusia dan mesin, di mana manusia berkedudukan sebagai konduktor nan memberikan arahan, konteks, dan makna, sementara AI menjadi orkestra nan menjalankan simfoni tugas dengan kecepatan tinggi. Eksperimen “perusahaan all-AI” ini bukanlah kegagalan, melainkan pelajaran berharga. Ia mengingatkan kita bahwa di kembali setiap algoritma nan canggih, kita tetap memerlukan sentuhan manusia: untuk mengarahkan, mengoreksi, dan memastikan bahwa semua teknologi ini pada akhirnya melayani tujuan nan manusiawi. Tanpa itu, nan kita miliki hanyalah mesin nan sibuk sendiri, berbincang tanpa henti ke dalam kekosongan.